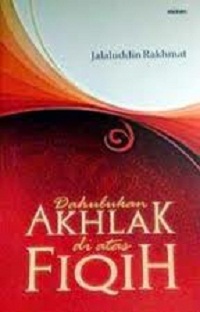
Saya harus mengingat kembali pengalaman hidup saya. Saya dilahirkan dalam keluarga nahdliyin. Kakek saya punya pesantren di puncak bukit Cicalengka. Ayah saya pernah ikut serta dalam gerakan keagamaan untuk menegakkan syariat Islam. Begitu bersemangatnya, beliau sampai meninggalkan saya pada waktu kecil dan bergabung dengan para pecinta syariat. Saya lalu berangkat ke kota untuk belajar, dan bergabung mula-mula dengan kelompok Persatuan Islam (Persis) dan masuk kelompok diskusi yang menyebut dirinya Rijâlul Ghad, atau pemimpin masa depan.
Pada saat yang sama, saya juga bergabung dengan Muhammadiyah, dan dididik di Darul Arqam Muhammadiyah, dan pusat pengkaderan Muhammadiyah. Dari latar belakang itu, saya sempat kembali ke kampung untuk memberantas bid’ah, khurafat, dan tahayul. Tapi sebetulnya, yang saya berantas adalah perbedaan fikih antara fikih Muhammadiyah dengan fikih NU orang kampung saya. Misi hidup saya waktu itu saya rumuskan singkat: menegakkan misi Muhammadiyah dengan memuhammadiyahkan orang lain.
Tapi apa yang kemudian terjadi? Saya bertengkar dengan Uwa’ (paman) saya yang masih membina pesantren, dan penduduk kampung. Sebab, ketika semua orang berdiri untuk salat qabliyah Jumat, saya duduk secara demonstratif. Saya hampir-hampir dipukuli karena membawa fikih yang baru itu. Singkat cerita, melalui pengalaman hidup, saya menemukan bahwa fikih hanyalah pendapat para ulama dengan merujuk pada sumber yang sama, yaitu Alqur’an dan sunnah. Hanya saja, kemudian berkembang pendapat yang berbeda-beda. Kekeliruan saya waktu itu: berpikir bahwa fikih itu sama dengan Alqur’an dan sunnah. Artinya, kalau orang menentang Alqur’an dan sunnah, jelas dia kafir. Tapi kalau hanya menentang pendapat orang tentang Alquran dan sunnah, kita tidak boleh menyebutnya kafir. Itu perbedaan tafsiran saja.
Karena itulah kemudian saya berpikir bahwa sebenarnya ada hal yang mungkin mempersatukan kita semua, yaitu akhlak. Dalam bidang akhlak, semua orang bisa bersetuju, apapun mazhabnya. Lalu saya punya pendirian: kalau berhadapan dengan perbedaan pada level fikih, saya akan dahulukan akhlak. Kalau datang ke jamaah NU yang qunut subuh, demi ukhuwwah dan memelihara akhlak di tengah-tengah saudara saya, saya akan ikut qunut, walau saya misalnya orang Muhammadiyah yang tidak qunut. Tapi, ketika bergabung dengan orang-orang Muhammadiyah, saya mungkin tidak qunut demi menghargai jamaah sekitar saya. Itu yang saya maksud mendahulukan akhlak di atas fikih.
JIL: Akhlak di sini dalam makna seperti apa, Kang? Bukankah pandangan tentang akhlak juga berbeda-beda dan cenderung sektarian juga?
Menurut saya, akhlak sebenarnya tidak ada yang sektarian. Saya percaya, tidak ada relativisme moral, termasuk relativisme akhlak. Ada yang mengatakan bahwa akhlak itu relatif. Menurut saya, orang baik yang menurut orang lain bukan orang baik itu tidak ada. Apakah membantu orang lain, menyebar cinta kasih, menolong mereka yang teraniaya, baik menurut mazhab tertentu, tapi buruk menurut mazhab lain? Saya ingin tahu: adakah akhlak yang sektarianistis? Beri saya satu contoh agar saya tidak kebingungan. Katanya, orang bingung membaca buku saya, karena definisi akhlaknya membingungkan. Menurut saya, akhlak tidak usah didefinisikan. Sebab semua orang tahu mana akhlak baik dan mana yang buruk. Yang ingin saya tahu: kira-kira, apa akhlak yang baik menurut satu mazhab tapi buruk menurut mazhab lain?
JIL: Apakah dalam menentukan akhlak tidak akan terjadi perbedaan standar?
Menurut saya, boleh saja orang lain memakai standar berbeda-beda. Tapi, standarnya adalah akhlak yang disepakati bersama. Kalau bicara tentang akhlak, saya bicara tentang sesuatu yang kebaikannya disepakati bersama. Itulah yang disebut nilai-nilai universal, universal values. Dalam setiap agama, termasuk Islam, terdapat nilai-nilai universal itu. Kita bisa berbagi, hatta dengan agama lain dalam soal nilai-nilai universal ini. Kalau dianalogikan dengan hukum, jadinya kira-kira begini. Di hukum itu, sebenarnya ada masalah antara kepastian hukum dan keadilan. Kalau kita berpegang pada aksara, kepada hukum secara letterlijk, akan ada suatu situasi di mana hukum menjadi tidak adil. Di situlah kepastian hukum bertabrakan dengan ketidakadilan. Analogi itu bisa mengibaratkan soal akhlak dan fikih. Akhlak menurut saya adalah sesuatu yang pasti. Semua orang sepakat soal keutamaan akhlak. Yang tidak sepakat adalah tentang fikih. Jadi, daripada berpegang pada fikih yang tidak pasti, lebih baik kita berpegang pada akhlak yang sudah pasti.
JIL: Kang Jalal, apakah buku-buku fikih betul-betul alpa membahas soal akhlak? Saya kira, buku fikih Imam al-Ghazali, Bidâyatul Hidâyah, juga cenderung membahas soal akhlak.
Memang, al-Ghazali sendiri misalnya bercerita tentang sirr, ataurahasia dari semua aturan fikih. Misalnya, puasa bukan sekadar menahan makan dan minum, tapi juga mengendalikan diri dari segenap perbuatan yang dilarang Allah. Jadi ada juga unsur akhlaknya. Tapi kalau kita bicara fikih sebagai ilmu, tentu tidak begitu. Bacalah buku fikih apa saja, misalnya Kitâbul Fiqh `alal Madzâhib al-‘Arba`ah. Di situ sudahtidak ada lagi pembicaraan soal akhlak. Dan ingat, Imam al-Ghazali pun berbicara di situ dalam konteks pengajaran tasawuf; mencari rahasia di balik ritual, di balik syariat. Soal syariatnya sendiri tetap berpusat pada fikih. Sampai ada yang mengatakan fikih itu soal al-hukm biz dzawâhir. Jadi, fikih itu secara umum memang berpegang teguh pada hal-hal yang lahiriah. Sementara, al-Ghazali sendiri membedakan antara khalq dan khuluq, walaupun dalam penulisannya Arabnya sama. Khalq adalah gambaran lahir atau tubuh kita, sementara khuluq gambaran batin.
Jadi, khalq itu urusan fikih, sementara khuluq “sepatutnya” diurus oleh tasawuf. Artinya, dalam kenyataan, fikih terpisah dari studi akhlak, walau para ulama membahas fikih sekaligus menyertakan akhlak sebagai ilmu. Tapi yang ingin saya tekankan: walau kita mungkin belajar fikih tidak boleh terlepas dari akhlak, bahkan fikih harus menyempurnakan akhlak, dalam kenyataan sehari-hari, kita tetap sering menemukan tuntutan fikih yang bertentangan dengan tuntutan akhlak. Misalnya, tuntutan fikih saya sebagai orang Muhammadiyah adalah: membaca qunut waktu subuh, bid’ah hukumnya. Tapi sekarang saya hidup dalam komunitas NU. Tuntutan fikih saya “jangan qunut subuh”, tapi jemaah NU di tempat saya mengangkat saya sebagai imam.
Kalau saya tidak punya tuntutan akhlak untuk menjaga silaturahmi dengan masyarakat sekitar, lalu saya tidak qunut, pecahlah silaturahmi saya dengan kaum nahdliyyin. Mereka bisa pada lari dan mengulang salat, karena perbedaan fikih. Makanya, daripada menimbulkan keributan, lebih baik saya dahulukan akhlak. Apakah qunut itu sunnah atau bid’ah, itu soal pendapat dan pilihan hadis.
Saya ingin beri contoh yang bagus dari tokoh al-Ikhwan al-Muslimun, Hasan al-Banna. Konon, al-Banna masuk sebuah masjid pada bulan puasa ketika orang-orang sedang bertengkar soal jumlah rakaat tarawih. Satu kempok bilang 11, yang lain condong ke 23 rakaat. Itu jelas pertengkaran fikih. Al-Banna lalu bertanya pada kelompok yang mendukung 11 rakaat: “Menurut kalian, apa hukumnya salat tarawih?” “Sunnah!” jawab mereka. Kepada yang 23 juga ditanya hal sama. Jawabnya: “Sunnah!” Lalu dia bertanya lagi: “Apa hukum bertengkar antara sesama kaum muslimin di masjid?” Semua sepakat menjawab “haram”. Al-Banna lalu menyadarkan mereka, “Mengapa kalian melakukan yang haram demi mempertahankan yang sunnah?” Artinya, sebenarnya al-Banna sedang menjalankan prinsip mendahulukan akhlak di atas fikih.
JIL: Ada yang bilang, kalau sedang memberantas bid’ah yang dilarang agama, tidak relevan lagi bicara akhlak. Bukankah Nabi menyebut “kullu bid`atin dlalâlah wa kullu dhalâlatin fin nâr”? Jadi ini soal memberantas kemungkaran.
Pertama kita harus definisikan dulu makna bid’ah, atau bagaimana ia didefinisikan di tengah masyarakat. Pada awalnya, bid’ah bermakna sesuatu yang tidak diperintahkan Rasulullah. Ini merujuk hadis Nabi yang diriwayatkan dalam Kitab Shahîh Bukhari, “Man ahdatsa fî mâ laitsa `alaihi min amrinâ fahuwa radd”. Artinya, semua hal yang tidak kami perintahkan harus ditolak. Jadi, kalau sesuatu itu tidak diperintahkan Rasulullah, itu namanya bid’ah. Saya kira, semua setuju soal itu.
Bahkan, dalam riwayat Nabi yang lain bid’ah itu disebut muhdatsât, sesuatu yang baru, yang tidak pernah ada di zaman Nabi. Hadisnya: “Alâ iyyâkum wa muhdatsâtil umûr”, atau jauhilah olehmu perkara yang baru-baru dalam agama. Sebab, setiap yang muh
dats itu bid’ah, dan setiap bid’ah sesat, dan setiap kesesatan akan ke neraka. Dulu ketika masih jadi kader Muhammadiyah, saya hapal sekali hadis itu. Jadi, bid’ah adalah sesuatu yang baru, yang tidak ada dalam perintah Rasulullah.
Tapi dalam perkembangan zaman dan pada kenyataan di masyarakat, yang disebut bid’ah itu ialah soal ibadah-ibadah. Dan anehnya, memang yang kita sebut bid’ah hanya ada dalam aspek ibadah, khususnya yang dijalankan orang lain, yang dalilnya tidak sama dengan kita. Maksudnya, qunut pada waktu subuh itu bid’ah, karena dalil tentang qunut subuh itu dla`îf atau lemah menurut orang Muhammadiyah, tapi tidak dla`îf menurut orang NU. Bahkan dalam sahih Bukhari dikatakan bahwa, Rasulullah qunut pada waktu subuh dan maghrib. Artinya, ada dalilnya, dan ada contoh Nabi. Yang pertama tadi juga punya contoh dari Nabi. Hanya saja, karena kita berbeda-beda dalam memilih hadis, maka yang mengambil hadis lain disebut bid’ah. Makanya, dalam soal seperti itu, perbedaannya kadang soal memilih hadis, atau dalam mendla`ifkan atau mensahihkan hadis.
Tapi, saya tetap setuju bahwa bid’ah yang benar-benar tidak ada keterangannya dalam Alqur’an dan hadis harus kita tolak. Tapi, kalau ternyata ada keterangannya dalam hadis, walau menurut kita dla`îf, kita harus bertoleransi pada orang lain untuk berpendapat dan menganutnya. Dan kalau kita menjalankan hal seperti itu, kita tidak berbuat dosa, tidak masuk neraka, dan tidak sesat.
Saya beri satu contoh kecil dari Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii. Suatu saat, Imam Sayfii salat di Baghdad yang dulu bernama Kufah. Dia tidak qunut pada waktu subuh. Lalu orang-orang bertanya: “Kenapa Anda tidak qunut?” Imam Syafii menjawab, “Aku menghormati shâhib tilkal maqbarah” (penghuni kuburan di situ). Ketika itu, Imam Abu Hanifah sudah meninggal dunia dan orang di sekitar situ tetap mengikuti pahamnya. Maka, demi menghormati Abu Hanifah, Imam Syafii tidak membaca qunut. Menurut saya, itu adalah prinsip mendahulukan akhlak di atas fikih.
JIL: Mengapa umat Islam lebih mementingkan fikih daripada akhlak?
Saya tidak tahu apakah telah membuat beberapa alasan dalam buku saya soal itu atau tidak. Buku saya itu sebenarnya terbagi dua. Pertama membahas mengapa kita harus mendahulukan akhlak di atas fikih, berujung pada contoh Rasulullah, para sahabat, dan para imam mazhab. Pada bab kedua saya menceritakan târîkhut tasyrî`al-islâmî atau sejarah legislasi hukum Islam dengan al-manhaj al-naqdî. Jadi buku ini mencoba mengkritik ushul fikih juga.
Kita ini selalu merasa yakin bahwa fikih kita yang paling benar dan fikih orang lain keliru. Itu sebenarnya bersumber dari kepercayaan yang berlebih-lebihan akan kebenaran fikih kita. Padahal, fikih itu dalam prosesnya selalu membuka ruang kritik. Dulu, Imam Syafii mengkritik konsep istihsân mazhab Abu Hanifah. Kalau cara dan argumentasi Imam Syafii itu kita gunakan sekarang, dia bisa dipakai untuk mengkritik konsep qiyâsh yang diajarkan Imam Syafii sendiri. Jadi ushul fikih itu selalu membuka peluang kritik.
Apa arti semua itu? Artinya, kita harus tawâdlu` atau rendah hati; bahwa semua fikih mengandung unsur manusia di dalamnya. Karena itu, semua fikih mengandung unsur kesalahan. Anda tentu tahu ucapan seorang ulama: fikih dia benar, tapi mengandung kemungkinan keliru (ra’yî shawâb wa yahtamilul khata’); begitu juga sebaliknya. Saya tidak tahu sejak kapan aliran mushawwibûn itu tersingkir dari masyarakat dan diambil-alih aliran mukhatti’ûn. Tapi tampaknya, aliran yang suka menyalah-nyalahkan orang itu muncul sejak adanya aliran pembaharuan yang juga suka menyalah-nyalahkan.
JIL: Apakah mindset atau paradigma berpikir tertentu juga menjadi soal?
Ya, betul. Saya pernah cerita tentang dua paradigma atau cara memandang persoalan. Pertama, paradigma akidah. Dalam paradigma ini, hanya ada satu akidah yang benar, dan hanya satu kelompok yang masuk surga. Dengan begitu, hanya ada satu kebenaran. Baik-buruknya seseorang diukur berdasarkan akidah. Padahal, walau banyak orang mengatakan akidah itu ushûl atau sesuatu yang pokok, ia seringkali juga bersifat furû’ atau cabang. Jadi ada furû`-furû` akidah.
Ini sebenarnya penjelasan untuk orang awam karena mereka sering ditipu bahwa akidah adalah ushûl, dan kalau akidah seseorang tidak sama, maka ia akan kafir dan seluruh amal salihnya tidak diterima Tuhan. Orang kemudian diukur dari akidah; kalau akidahnya sama dengan kita, dia akan sama mulianya. Kalau akidahnya tidak sama, dia langsung direndahkan, mungkin disamakan dengan binatang, bahkan dihapuskan dari segala unsur kemanusiaannya. Seluruh hak-hak dia sebagai manusia hilang karena urusan akidah.
Nah, paradigma yang saya promosikan adalah paradigma akhlak. Dalam paradigma kedua ini, manusia selalu diukur dari kemuliaan akhlak, kontribusinya terhadap kehidupan sosial, dan pemihakannya pada keadilan. Itulah paradigma akhlak. Menurut saya, paradigma ini lebih bersih dari manipulasi pemikiran. Paradigma akidah bisa ditafsirkan macam-macam. Misalnya, ziarah kubur itu menurut sebagian orang musyrik. Tawâshul dan tabarruk juga dianggap kemusyrikan. Begitulah paradigma akidah. Akibat lanjut paradigma ini, kalau betul-betul konsisten diterapkan—untungnya, kebanyakan tidak konsisten—bisa menjurus pada perpecahan luar biasa di kalangan umat Islam.
JIL: Kang Jalal, kalau ditanya mana yang lebih baik, muslim yang taat ibadahnya tapi tidak baik akhlaknya, atau yang kurang taat tapi berakhlak baik, mana yang Anda pilih?
Dulu saya selalu menjawab soal ini dengan cara mengelak. Saya katakan, yang baik ialah yang salat dan akhlaknya bagus. Tapi jawaban itu tidak jujur, karena pilihannya hanya dua: (a) salatnya baik, tapi berakhlak buruk; (b) salatnya buruk, tapi akhlaknya baik. Jadi tidak ada pilihan (c) yang salat dan akhlaknya baik di situ. Kalau jawaban berkelit itu saya berikan dalam ujian, jelas saya tidak lulus, karena memang tidak ada dalam kategori.
Karena itu, sekarang saya akan menjawab: lebih baik yang akhlaknya bagus sekalipun salatnya buruk, ketimbang salatnya bagus tapi akhlaknya buruk. Dalilnya: satu, karena sebaik apapun salat kita akan terhapus pahalanya oleh akhlak yang buruk. Haji juga begitu. Sekalipun ia dijalankan sebaik-baiknya, malah mungkin setiap tahun, kalau di dalam pelaksanaannya ada rafats, fusûq, dan jidâl, hajinya tidak sah. “Faman faradla fî hinnalhajja falâ rafatsa walâ fusûqa walâ jidâla fil hajj,“ Itu dalil Alqur’annya.
Dalam ayat lain juga disebutkan, kalau sedekah kita disusul dengan ucapan yang menyakiti hati, maka sedekahnya akan batal. Dalam Alqur’an diterangkan, “La tutbi’û shadaqâtikum bil manni wal ‘adzâ”, atau jangan kamu batalkan sedekahmu dengan menggerutu dan menyakiti hati orang yang menerima.
Alqur’an juga mengatakan, kalau orang menyakiti sesama manusia akan dilaknat Allah di dunia dan akhirat. Dalam surah al-Ahzâb: 56 dikatakan, “Innalladzîna yu’dzûnalLâh wa rasûlah la`anahumulLâhu fid dunyâ wal âkhirah, wa ‘a`adda lahum adzâban mubîna. Wallladzîna yu’dzûnal mu’minîna wal mu’minâti bighairi mâ iktasabû faqad ihtamalû buhtânan wa itsman mubîna”. Intinya, mereka yang menyakiti orang lain itu sedang menghapus seluruh amalnya.
Sebuah hadis qudsi juga mengatakan: “Ya Ahmad, katakan kepada orang-orang yang zalim itu agar tidak masuk rumah di antara rumahmu, karena sudah menjadi kewajiban bagi-Ku untuk menyebut orang yang menyebut namamu. Dan kalau seseorang menyakiti orang lain dan menyebut namamu, Aku akan menyebut namanya juga”. Dan di situ diterangkan, “wa dzikrî iyyâhu ‘an al`anahu” (zikirku padanya adalah: Aku melaknat dia). Jadi, setiap kali orang salat, tapi akhlaknya buruk, suka menyakiti orang lain, maka setiap kali dia menyebut “Allahu akbar” dalam salat, Allah justru melaknatnya. Artinya, salatnya hanya berfungsi untuk mengumpulkan laknat Allah. Jadi, betapa kasihan orang yang salatnya baik tapi akhlaknya buruk, karena seluruh ibadah salatnya gugur.
Satu lagi nilai paling penting yang perlu disampaikan di bulan puasa ini adalah hadis yang termuat di kitab Ihyâ `Ulûmiddîn. Saat itu, kepada Rasulullah dilaporkan bahwa “Inna fulânah tashûmun nahâra wa taqûmul lailâ walâkin tu’dzî jirânaha bilisâniha” (ada seorang yang rajin puasa siang dan salat malam, tapi suka menyakiti tetangga dengan lidahnya). Apa kata Rasulullah? “Hiyâ fin nâr” (dia di neraka). Kesimpulan saya: lebih bagus yang akhlaknya baik tapi salatnya jelek, ketimbang salatnya baik tapi akhlaknya jelek.
JIL: Bagaimana kalau ada yang mengatakan itu karena salatnya memang tidak benar. Kalau salatnya sudah benar, semua akan benar?
Kita memang pernah mendengar hadis bahwa “yang pertama kali diperiksa dari seorang hamba di akhirat kelak adalah salatnya”. Artinya, “Ídza shaluhat, shaluha sâ’iru `amalih, wa idzâ fasadat, fasada sa’iru `amalih,” (kalau beres salatnya, bereslah seluruh amalnya, dan jika rusak, rusaklah seluruh amalnya). Hadis ini bisa diartikan bahwa kalau seseorang menjalankan salat dengan baik, pastilah akhlaknya akan baik. Tapi tadi kita berhadapan dengan pertanyaan yang contradictio in terminis; “salatnya baik, tapi akhlaknya buruk”. Karena itu, ada yang menjawab hal itu tidak mungkin. Sebab kalau salatnya baik, pasti akhlaknya akan baik.
Tapi, sayang kriteria salat yang baik itu sangat fiqhiyyah atau berbau fikih. Artinya, tetap saja bergantung pada mazhab yang mana. Menurut mazhab Syafii, salat yang baik adalah dengan qunut. Tapi menurut Hanbali, salat yang baik tanpa qunut, kecuali pada saat perang. Dan begitulah seterusnya. Artinya, ada asumsi kalau salat itu sesuai dengan mazhab tertentu, barulah ia dikatakan baik.
Saya pernah menemukan beberapa kitab yang berjudul Shalatun Nabi. Waktu saya baca, ternyata salat ala mazhab Hanafi. Saya beli lagi buku dengan judul yang sama; ternyata salat menurut mazhab Hanbali. Orang Syiah juga punya buku tuntunan salat ala Syiah. Judulnya juga senada, Shalatun Nabi. Jadi, apa yang disebut salat yang paling sesuai contoh Nabi itu, dan dengan itu menjadi salat yang paling baik, juga bergantung pada mazhab tertentu.
Yang kedua, dalam kenyataan sosial di masyarakat, kita tak jarang menemukan orang yang rajin dan khusuk salat, rajin haji, tapi juga khusyuk korupsi. Nah, apakah hadis itu salah dan Rasulullah keliru? Saya yakin, Rasulullah tidak salah. Yang salah adalah penafsiran kita terhadap hadis itu. Karena itu, tafsiran saya ialah: ukuran baik-buruknya salat bukan pada standar mazhab, tapi dilihat dari ukuran akhlaknya di tengah masyarakat. Kata Rasulullah, “Idzâ shaluhat, shaluha sâ’iru `amalih”.
Jadi, kalau ingin tahu baiknya salat seseorang, lihatlah amalnya di masyarakat. Kalau amalnya baik, itu berarti salatnya baik, tidak peduli apa mazhabnya. Jadi, test case-nya tetap di masyarakat. Kalau saya datang ke sebuah kampung dan bertemu seseorang yang akhlaknya bagus, tapi kebetulan fikihnya berbeda dengan saya, saya akan tetap menghormati dan mencium tangannya. Orang-orang yang dermawan akan saya cium tangannya, tidak peduli dari mazhab, bahkan agama apa pun. Tapi soal ini jangan dikomentari macam-macam; seperti ada maksudnya.
Sekarang tesis saya yang terakhir, bukan yang terbaru: hablun minalLâh atau hubungan baik dengan Tuhan itu diukur dari hubungan baik dengan sesama manusia (hablun minan nâs). Jangan ada yang merasa sudah takwa pada Allah hanya karena ibadahnya baik. Tapi, lihatlah apa kontribusi dia bagi kemanusiaan. Alqur’an sendiri mengatakan bahwa orang-orang yang membanggakan ritus-ritus agama tapi tidak ada buktinya dalam kehidupan bermasyarakat—misalnya tetap sombong, suka menindas, dan tidak punya empati pada penderitaan orang—mereka dianggap pendusta agama. Ayatnya: “Ara’aital ladzî yukaddzibu bid dîn, fadzâlikal ladzî yadu`ul yatîm…” (Tahukah Engkau siapa para pendusta agama? Mereka adalah orang yang tidak peduli pada anak yatim…, Red).
Jadi, hablun minallâh juga akan rusak kalau hablun minan nâs kita rusak. Tapi jika hablun minan nâs seseorang baik, itu berarti hablun minalLâh-nya juga baik. Jadi ukuran hablun minalLâh adalah hablun minan nâs agar ukurannya bisa kita lihat. Sebab, ukuran hablun minalLâh itu tidak bisa kita lihat; bagaimana sih tali yang merentang kepada Allah itu?! Kalau tali yang merentang di antara sesama manusia, kita akan bisa melihatnya, dan ukurannya cukup banyak. []

 RSS Feed
RSS Feed
